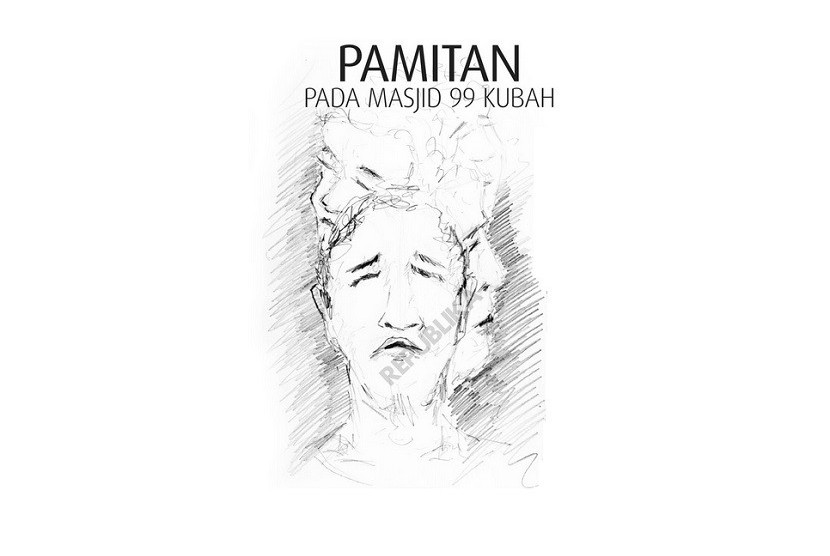Sebenarnya pikiran ayah yang demikian telah tersulut sejak Lebaran lalu. Lambat laun, pemikiran itu telah menjelma menjadi semacam penyesalan. Sia-sia banting tulang jauh-jauh hingga puluhan tahun, tetapi kembali ke kampung tanpa perubahan. Bilakah bulir-bulir keringat menjadi permata?
Apa perlu diaduk bersama air mata lagi? Beruntung ayah masih ingat kampung halaman. Kawan-kawan seperjuangannya telah hanyut dalam arus pensiun dan dihabisi usia lanjut di kampung orang. Mereka yang masih ingat tanah tumpah darahnya akan menepi dan banting setir mengamankan hari tua.
Karena itulah, ayah segera memutuskan kembali ke kampung, selagi tenaga masih tersisa. Walaupun, sebenarnya sudah terlambat karena baru merajut harapan demi tempat berteduh di hari tua. Padahal, masa-masa ayah masih bugar, tempat tinggal bahkan yang lebih memadai dari ini pun mudah dimiliki karena tanah-tanah baru bagi pegawai aktif telah tersedia dengan jaminan.
Sudah tak dapat kuhitung setiap ayah memasuki tempat baru pasti tersedia dengan rumah baru yang tidak lumutan seperti ini. Kala itu, jaminan ayah di perantauan layaknya tuan tanah yang bebas melepas dan memiliki tanah demi pendidikan anak-anaknya. Wajarlah keluarga turut diboyong ke perantauan.
Pada akhirnya, kompleks perumahan yang nyaris mangkrak inilah menjadi pilihan. Kalau bukan sekarang, entah kapan lagi, pikir Ayahku. Tempat ini menjadi pilihan karena dinilai lebih bijak di garis tak berpihak. Tak dekat dengan keluarga Ayah, demikian pula Ibu.
Bisa saja berdampingan hidup dekat dengan keluarga besar karena tanah warisan masih ada, tetapi hari tua ha rapannya hidup tenang, jauh dari keributan. Rasa malu pun dipertaruhkan karena orang yang pernah merantau mestinya berpikir lapang.
Mungkin ayah dan ibu pun memilih tempat itu agar tetap menumbuhkan benih-benih kerinduan. Karena ada mutiara kata para perantau: jagalah jarak dengan keluarga bila engkau ingin merasakan apa arti merindu.
Berusaha aku membesarkan harapan ayah. Biarlah masa-masa pensiun ini dicurahkan untuk menata keluarga kecil nan bahagia. Seperti niat awal untuk kembali ke tanah tumpah darah: rindu pulang kampung.
Rerata cita-cita perantau seperti itu. Hari ini giliran aku, Dewi, dan Arlan yang mewarisi jejak ayah serta ibu menyulam napas kehidupan di negeri orang. Mungkin inilah satu-satunya warisan ayah yang masih kujalani.
Tak terasa, kini sudah hari Lebaran yang keempat. Aku, ayah, ibu serta keluarga yang lain masih gelisah menanti kendaraan silaturahim. Pagi buta, keluarga merapat untuk turut serta.
Jam dinding dan jam tangan sudah di tengok berkali-kali hendak memastikan mesin jam yang putus atau empunya mobil mabuk kue le baran hingga tergelincir menembus batas waktu. Ayah dan ibu masih saja asyik bercerita untuk menghibur rasa jenuh. Episode demi episode cerita telah dilalui, tetapi mobil tak kunjung tiba.
Bila pemesanan gagal, berarti ini pembatalan yang ketiga. "Biar banyak uang, kalau mobil yang dipesan tidak ada, sama saja bohong," lagi ayah menggerutu.
"Mobil yang dipesan, sudah didahului orang lain, memang musim Lebaran seperti ini, sang peminjam mesti berhubungan langsung dengan empunya mobil, bila tak ingin ditelikung oleh orang lain karena tibalah masanya berlomba memesan kendaraan demi silaturahim, " pungkasku lebih menjelaskan.
Di penghujung Lebaran ini kembali akan kutatap kampung dari jauh sembari melambaikan tangan dengan ucapan selamat tinggal. Koper dan oleh-oleh Lebaran telah siap diboyong menuju arena pertarungan sebelas bulan.
Kali ini kompetisi semakin keras karena melibatkan para perantau dari negeri asing. Mereka telah siap menggusur siapa pun yang dinilai tak siap bersaing. Makanya, tanah seberang tampak tak bertepi karena diserbu pencari kerja dari segala penjuru. Pagar pembatas harus rela diterobos untuk memaksa negeri berlari. Bahasa dan cerita tidaklah penting, lebih utama mampu bekerja sesuai dengan bulir keringat yang dihitung.
Si Bungsu, Arlan sudah siap dengan kopernya. Dia termasuk perantau debutan yang diancam oleh waktu. Bersama kawannya belajar menyusuri tol langit lewat pesawat yang suntuk di ujung waktu.
Kasihan, sebagai kawan yang baru, Arlan tergantung padanya. Padahal, sikapnya yang pongah hasil dari kompetisi yang keras. Paras le baran pun tak tampak padanya. Aku menduga dia menjadi orang asing pertama di kampungnya.
Satu per satu saudara telah kembali ke tanah rantau. Tak terkecuali saudara perempuanku, Dewi. Hanya aku yang kembali melewati jalur laut, melintasi Masjid 99 kubah sebagai ikon baru kota Phinisi. Seolah hanya aku yang pamitan padanya. Sembari berjanji: semoga Lebaran ke depan aku masih dapat mengenal dan menghitung kubah itu dalam wiridku walaupun terpaut jarak.
Tiba-tiba ponselku bergetar. Seperti biasa Ibu menanyakan kabar perjalananku. Aku terkejut mendengar kabar tentang Ayah yang turut pula mengangkat koper untuk merantau. Bukankah tidak sebaiknya dia meluruskan niat menjalani masa pensiun di kampung. Mungkin Ayah bosan dengan cerita di rumah itu sehingga bermaksud membongkarnya. Kalau demikian halnya, aku lebih kasihan pada Ibu yang ditinggal sendiri.
TENTANG PENULIS; MUSAFIR KELANA
Pemilik hobi membaca dan melukis inilahir di Atari Jaya, Sultra. Pembimbing Komunitas Puisi Santri OLSN (Olimpiade Literasi Siswa Nasional) Al Binaa Islamic Boarding School, Bekasi. Cerpennya pernahditerbitkan di harian Papua: Mudik Pada Alam dan Taring-Taring Malaria. Puisi Republika: pena Tua