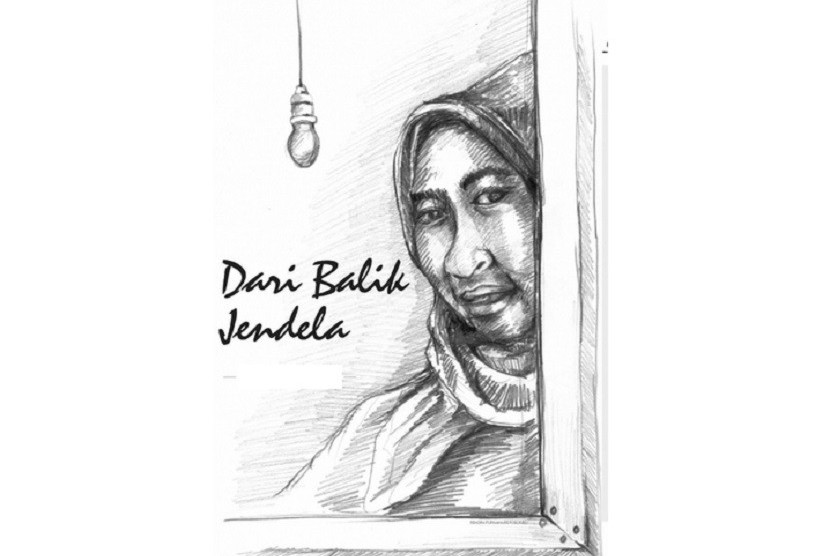Adalah aku, salah seorang yang selalu menantikan sore tiba. Akan bahagia ketika melihat ujung-ujung pohon berwarna kekuningan. Tapi yang sebenarnya paling kusukai dari senja ialah ketika ada sosokmu di tiap jengkal hidupku. Walau kenyataannya kisah itu sudah terlalu usang untuk dibahas.
Lalu … biarkan saja tetap kugenggam setiap kenangan yang pernah ada. Yakni tentang kejora di ufuk barat yang berwarna jingga. Yang seolah selalu menarikan aksara-aksara indah untuk setiap pertemuan kita.
Socaku kini mengembun hebat. Keberadaanku di balik jendela senja ini tak hanya menyeretku pada kenangan indah, tapi juga menggali kembali luka lama yang sebenarnya sudah berulang kali kukubur dengan kedalaman sampai pasak bumi.
Kudapati pohon yang ujungnya kekuningan melambai-lambai diterpa angin sore. Dulu, keadaan begini akan menambah syahdu pertemuan kita, tapi sekarang terasa lebih mengiris hati. Menyadarkanku bahwa semua itu tak lagi mungkin terulang, semua itu hanya ada dalam ruang kecil di hatiku yang disebut kenangan.
***
“Jodohkan saja Khumaira dengan Fajar, Pak. Anaknya baik, sopan, dan mapan. Setara dengan kita.”
Mendengar itu, aku tersenyum malu-malu. Mengangguk sedikit tanpa seorang pun melihat. Bukan karena tentang statusmu yang mapan, atau tentang pesonamu yang rupawan. Tidak, sungguh tidak. Melainkan jika benar kita berjodoh, maka akan ada pahala yang bertumpuk untukku yang mau mengabdi padamu. Memperlakukanmu menjadi sebenar-benarnya suami, sebenar-benarnya pemimpin. Yang insya Allah akan membimbingku menyusuri sirotol mustaqim ke jannatullah. Sungguh teramat menyenangkan meski baru sebuah bayangan.
“Tapi apa ya Si Fajar mau?”
Bapak bersitatap dengan ibu. Masih ragu. Mengingat anaknya adalah perempuan. Tak mungkin hendak melamar. Kodrat perempuan hanya menunggu. Menunggu dan menunggu untuk dipinang.
“Ya jelas mau, keluarga kita kan terpandang. Khumaira juga amat cantik. Tak kalah dengan gadis-gadis kota tempat Fajar bekerja.”
Hentakan perpaduan sendok dan piring membentuk dentingan-dentingan khas insan-insan yang menikmati santapan malam. Menyaingi pembicaraan serius Bapak dan Ibu.
“Lelaki desa saja banyak yang mengantre ingin memperistri Khumaira, Pak. Mana mungkin Fajar sampai hati menolak? Mending segera diijabkan saja keduanya.”
Ibu masih mengeyel. Bapak sedikit tersedak. Mendengar arah pembicaraan ibu yang makin lama, makin menyombongkan diri.
“Mbok ya ditanyakan dulu pada yang bersangkutan. Ini sudah bukan musim perjodohan lagi, Bu.”
Bapak tak kalah ngeyel. Mencoba menjelaskan pada wanita yang telah lebih dari dua puluh tujuh tahun menjadi istrinya. Aku yang berada di antara keduanya hanya memperhatikan. Menoleh kiri saat ibu bicara, lantas menoleh kanan saat bapak menjawab.
“Bapak kan kiai di kampung ini, tidak mungkin pula keluarga Fajar menolak kita. Kalau Khumaira sudah pasti menyetujui usulan Ibu. Lha wong sudah lama kesemsem. Iya kan, Nduk?”
Aku menelan paksa nasi yang sebenarnya belum lembut dikunyah. Terasa sungsang di tenggorokan. Maka, kudorong secepatnya dengan air sebelum aku mendelik karena tersedak.
“In-injih, Bu’e.”
Gagap kujawab.
Sebagai Ibu, tak heran jika beliau teramat paham dengan perkembanganku. Termasuk ketika aku meresapi ada yang terasa ganjal di hati ketika tak sengaja berpapasan denganmu. Dada terguncang sebab jantung yang hebat berdebar. Ya, sejak awal kedatanganmu aku memang telah mememe… ah, entahlah. Hal itu belum terlalu kupahami. Bukankah yang harus kupahami terlebih dahulu adalah hafalan Alquran yang belum khatam hingga sekarang?
Suatu waktu, aku memperhatikan sosok yang membuat air bergemericik di padasan. Tampungan air untuk berwudlu itu tampak ada yang berbeda —padahal biasanya juga seperti itu, dipakai orang untuk berwudlu. Tapi lihatlah! Di sana ada sosokmu … iya, itu kau. Apa orang tua kita telah diam-diam berbicara tentang rencana sunnah Rasulullah itu? Lantas kita sama-sama tak diberitahu, supaya hingga pada saat tiba waktunya, kita menganggap itu sebagai hadiah kejutan yang begitu indah.
“Assalamu’alaikum, Jingga.”
Sembari membenarkan peci, kaututurkan itu. Aku kebingungan setengah mati, menoleh ke sana ke mari, mencari sosok yang kaupanggil Jingga. Ternyata sejak aku masih melamun, langkahmu sudah sedemikian dekat menghampiriku yang berdiri mematung di balik jendela kamar—memerhatikanmu.
“Haha, kau begitu polos, Khumaira. Oh, iya. Assalamu’alaikum. Tadi belum sempat kau jawab salamku. Bukankah aku mendoakan supaya kau sejahtera, ayolah … giliranmu mendoakan lelaki yang akan jadi imam di setiap sujudmu ini untuk sejahtera juga.”
Kau teramat biasa merayu gadis kota sepertinya. Lancar sekali bualan itu kauucapkan.
“Wa-wa’alaikum salam, Kang. Mungkin Kang Fajar salah orang. Di sini Khumaira sendiri, tak ada Jingga. Dan seingat Khumaira pun tak ada santri yang bernama Jingga.”
Kau masih tetap menatapku tanpa canggung. Menyemburatkan senyum penuh arti dengan gelengan kepala. Sementara aku makin tertunduk dalam. Malu kaupandang seperti itu.
“Jingga itu kau, Khumaira. Gadis jendela yang senang melihat keindahan senja yang berwarna jingga.”
Aku tertunduk malu. Bagaimana pun aku tak boleh berlama-lama berbincang berdua selayak ini. Takut jika hati dikuasai iblis yang berbisik sembarangan.
“Haduh … haduh ampun, Pak Kiai!” teriakmu tiba-tiba.
Sontak aku mencuri tatap apa yang sebenarnya terjadi. Senyumku tak kuasa merekah. Satu jeweran mendarat di telingamu. Bapak yang melakukannya.
Dia menarik telingamu menuju tempat shalat laki-laki, mau tak mau kau mengikuti langkahnya agar kupingmu tak putus. Kejadiannya persis seperti saat Shihab—adikku—menggoda santriwati yang mondok. Eh, itu berarti kau sudah setara dengan Shihab, sudah sama dianggap anaknya.
Di kesempatan yang lain, kudengar suaramu. Suara seorang lelaki dewasa yang masih keteteran membedakan sa, sya, dan shod. Pasti dulu saat kecil kau senang bolos TPQ, jadinya sebesar itu—bahkan di saat sudah ada embel-embel akan menjadi imamku—kau masih belajar Yanbu’a.
“Mbok ya kalau belajar itu yang serius to, Le. Apa tidak malu dilihat anak-anak yang masih kecil itu? Mereka saja sudah lancar membaca Alquran.”
Celoteh Bapak kentara menyindirmu. Namun memang benar, bukan? Bahkan si kecil Nabila lebih lancar bacaannya dibanding dirimu.
“In-injih, Pak. Sama putri Pak Kiai saja saya serius. Apalagi hanya belajar Yanbu’a.”
Kau dengan ekspresi cengengesan memasang rayuan gombal pada Bapak. Cari perkara kedua kalinya. Maka mendaratlah jeweran di telinga satunya biar tidak saling iri.
“Ampun, Pak Kiai Calon Mertua.”
“Kapok?”
Kau tak berdaya menjawab, hanya mengangguk.
“Kau pernah menjadi imam shalat, Le?”
Beberapa minggu setelahnya, kau telah memimpin shalat kami dengan bacaan fasih. Meski setelah membaca Al-Fatihah hanya terlantun Al-lkhlas.