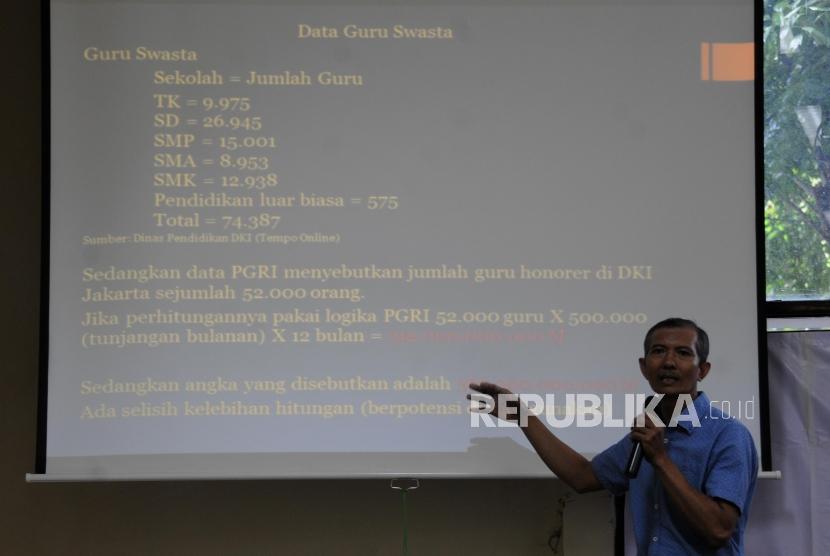REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat beberapa hal kritis mengenai kondisi masyarakat saat ini, terutama dalam hal pendidikan, sehingga dapat menimbulkan adanya potensi tumbuhnya radikalisme di lingkup pendidikan. Catatan didapatkan dalam diskusi dan kajian-kajian FSGI untuk menangkal radikalisme yang membawa anak dalam aksi terorisme.
Pertama, kekerasan dalam bentuk apapun semestinya tidak lagi terjadi di masyarakat, apalagi di dunia pendidikan. Ideologi radikalisme, yang berujung dengan aksi kekerasan, berawal dari cara pandang yang tidak menghargai perbedaan.
“Merasa bahwa pendapatnya, diri atau kelompoknya yang paling benar dan anti terhadap pluralitas,” ungkap Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam siaran pers yang diterima Republika, Ahad (20/5).
Dia mengatakan, bibit-bibit radikalisme saat ini sudah tumbuh sejak dini di sekolah melalui pendidikan dan pembelajaran di kelas yang tidak terbuka terhadap pergulatan pendapat dan cara pandang. Sistem pembelajaran yang tidak didesain menghargai pendidikan dapat membuat siswa dan guru terjebak pada intoleransi pasif.
Intoleransi pasif, yaitu perasaan dan sikap tidak menghargai akan perbedaan suku, agama, ras, kelas sosial, pandangan kegamaan dan pandangan politik, walaupun belum berujung tindakan kekerasan. “Model intoleransi pasif inilah yang mulai muncul di dunia pendidikan kita,” kata Heru.
Catatan kedua, guru terjebak kepada pembelajaran yang satu arah. Heru berpendapat, praktik pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru (teacher centered learning).
Dia menerangkan, siswa hanya mendengarkan guru menerangkan pelajaran. Ini membuat memunculkan di mana guru mengetahui dan siswa tidak mengetahui.
Ini akan menghasilkan relasi pembelajaran yang menempatkan guru sebagai superior dan siswa inferior. “Tidak tercipta ‘pembelajaran dialogis’ antara siswa dan guru,” kata dia.
Heru berujar penyemaian radikalisme terjadi ketika guru terbiasa mendoktrin pelajaran, apalagi dalam ilmu sosial dan agama. Sebab, tidak terbangun suasana pembelajaran dialogis, yakni mendengarkan pendapat argumentasi siswa.
FSGI menemukan ada guru yang setiap hari mengunggah hoaks di akun media sosialnya. Guru ini juga aktif membagikan tautan dan video bermuatan kebencian SARA.
Catatan ketiga, keterbukaan siswa terhadap praktik intoleransi berkembang ketika guru membawa pandangan politik pribadinya ke dalam kelas. Beberapa guru mengajar sambil menjelaskan materi kemudian menyisipkan pilihan-pilihan politik bahkan sikap politik pribadinya terkait calon presiden.
Ada juga yang berkomentar terkait aksi terorisme yang terjadi bahwa ini adalah pengalihan isu atau mendukung konsep negara khilafah. “Bahkan, bersimpati terhadap ISIS,” kata Heru.
Selanjutnya, dia menjelaskan, masuknya bibit radikalisme ke sekolah karena sekolah cenderung tidak memperhatikan secara khusus dan ketat perihal kegiatan kesiswaan, apalagi terkait keagamaan. Selain itu, juga ditambah intervensi alumni dan pemateri yang diambil dari luar sekolah tanpa screening oleh guru atau kepala sekolah.
Catatan terakhir, bibit radikalisme ke sekolah karena sekolah cenderung tidak memperhatikan secara khusus dan ketat perihal kegiatan kesiswaan, apalagi keagamaan. Hal yang membuat buruk keadaan, yakni intervensi alumni dan pemateri yang diambil dari luar sekolah tanpa screening oleh guru atau kepala sekolah.
“Masuknya pemikiran yang membahayakan kebinekaan ini bisa dari alumni melalui organisasi sekolah atau ekstrakurikuler, pemateri kegiatan kesiswaan yang bersifat rutin, seperti mentoring dan kajian terbatas,” tutur Heru.